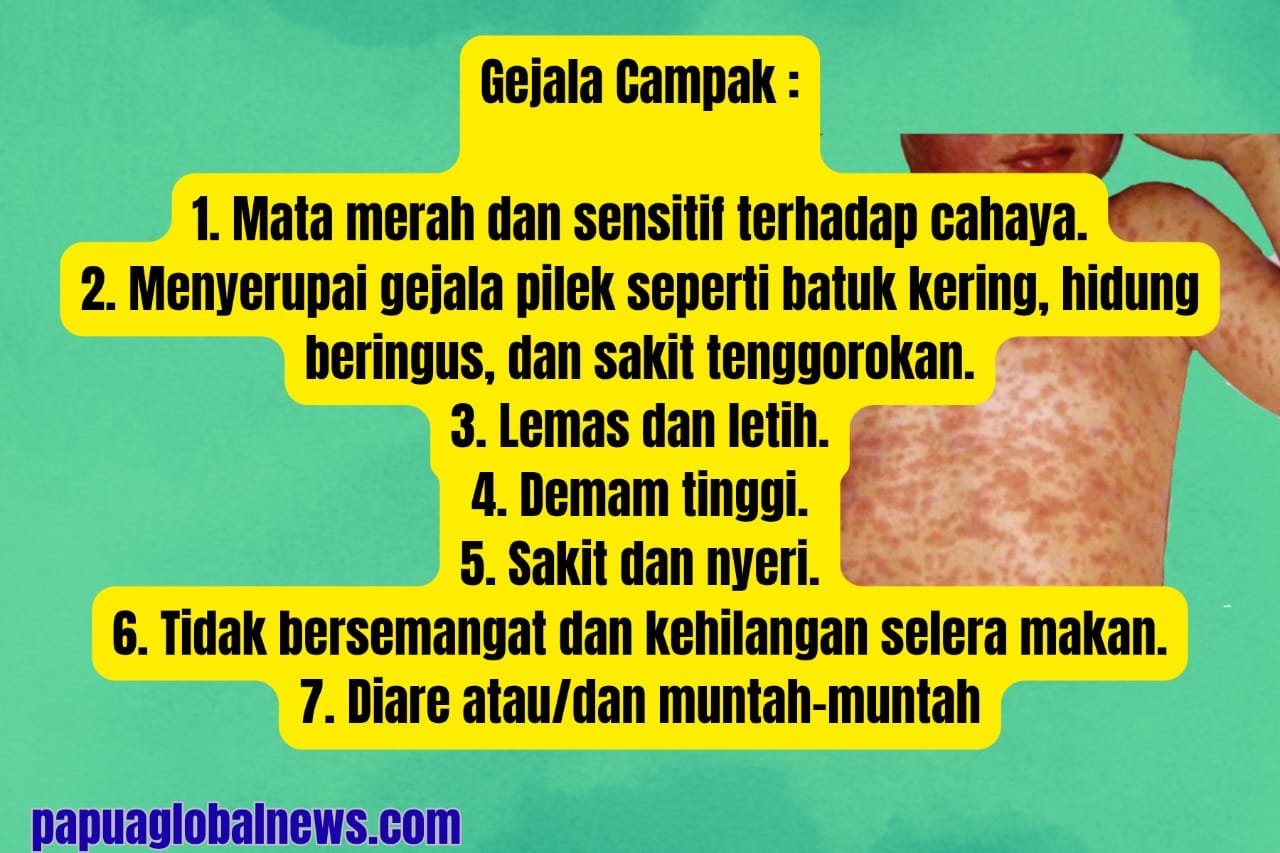APBD-P Rp6,8 Triliun: Keadilan Sosial yang Dipertaruhkan di Mimika
Kita dapat bertanya dengan kritis aspek keadilan substantif:
1. Apakah realisasi APBD-P Mimika telah mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial di daerah ini?
2. Bagaimana mengukur keberhasilan APBD-P dalam menjawab kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur kampung?
3. Apakah APBD-P mampu menciptakan lapangan kerja dan ruang ekonomi baru bagi mama-mama Papua, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, baik OAP maupun non-OAP?
4. Bagaimana memastikan agar dana pembangunan tidak tersedot ke proyek mercusuar yang minim manfaat sosial?
5. Apakah APBD-P benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, atau hanya sebatas instrument politik dan birokrasi?
6. Bagaimana kita bisa menilai APBD-P bukan hanya dari sisi legal-formal, tetapi dari moralitas keadilan untuk semua warga Mimika?
Ontologi Pengawasan
Fraksi PDI-P dalam sidang DPRK Mimika menyatakan akan melakukan “pengawasan ketat” terhadap jalannya APBD-P Rp6,8 triliun. Namun, pertanyaan kritisnya: apa makna pengawasan itu?
Pengawasan adalah jantung dari tata kelola keuangan daerah, termasuk APBD-P. Ada pihak yang diberi wewenang mengawasi: DPRK yang mengawasi eksekutif, ada BPK yang memeriksa, ada Inspektorat yang memantau internal.
Apakah pengawasan dilakukan terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil, ataukah hanya sebatas retorika politik untuk memperkuat posisi tawar fraksi? Pertanyaan tajam pun muncul: “Quis custodiet Ipsos custodes?” (siapa yang mengawasi para pengawas?), sebuah pertanyaan klasik dari filsuf Romawi, Juvenal, yang tetap relevan hingga hari kini. Ketika pengawas punya kuasa, siapa yang memastikan bahwa kuasa itu dijalankan dan tidak disalahgunakan? Di sinilah letak paradoks fungsi pengawasan itu. Dalam perspektif filosofis itu, rakyat adalah pengawas sejati bagi para pengawas. Mengapa? Karena kepentingan rakyat yakni keadilan sosial adalah roh dari kebijakan anggaran dalam wujud APBD-P.
Mimikia dan Luka Ekstraktif
Mimika adalah wilayah kaya secara kasat mata. Di sinilah berdiri tambang emas raksasa dunia, PT Freeport Indonesia. Ironisnya, di tengah limpahan sumber daya, masyarakat asli Kamoro dan Amungme justru masih berhadapan dengan kemiskinan struktural, kehilangan ruang hidup, dan minim akses terhadap kesejahteraan.
Teori David Harvey (2003) tentang accumulatin by dispossession menjelaskan fenomena ini: akumulasi kekayaan lahir dari perampasan tanah, sumber daya, dan ruang hidup masyarakat adat. Dalam konteks ini, APBD seharusnya hadir sebagai instrumen redistribusi keadilan, untuk menutup luka ekstraktif yang sudah lama diderita rakyat Mimika.
APBD-P sebagai Ruang Pertaruhan
Pada akhirnya, APBD Mimika bukan sebatas dokumen fiskal, melainkan ruang pertaruhan keadilan sosial. Dengan nilai Rp6,8 triliun, ada dua jalan yang mungkin ditempuh:
1. Jika salah kelola, APBD-P hanya akan memperkuat elite, memanjakan birokrasi, dan melanggengkan ketimpangan.
2. Jika benar dikelola, ia bisa menjadi jembatan rekonsiliasi sosial-ekonomi, menghadirkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi rakyat Mimika, terutama masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.
Keadilan sosial bukan hanya retorika dalam konstitusi, melainkan tanggung jawab nyata. APBD-P Rp6,8 triliun di Mimika adalah ujian: apakah negara benar-benar hadir untuk rakyat, atau malah memperpanjang dominasi kuasa di atas penderitaan mereka. (Isi tulisan tanggung jawab penulis)