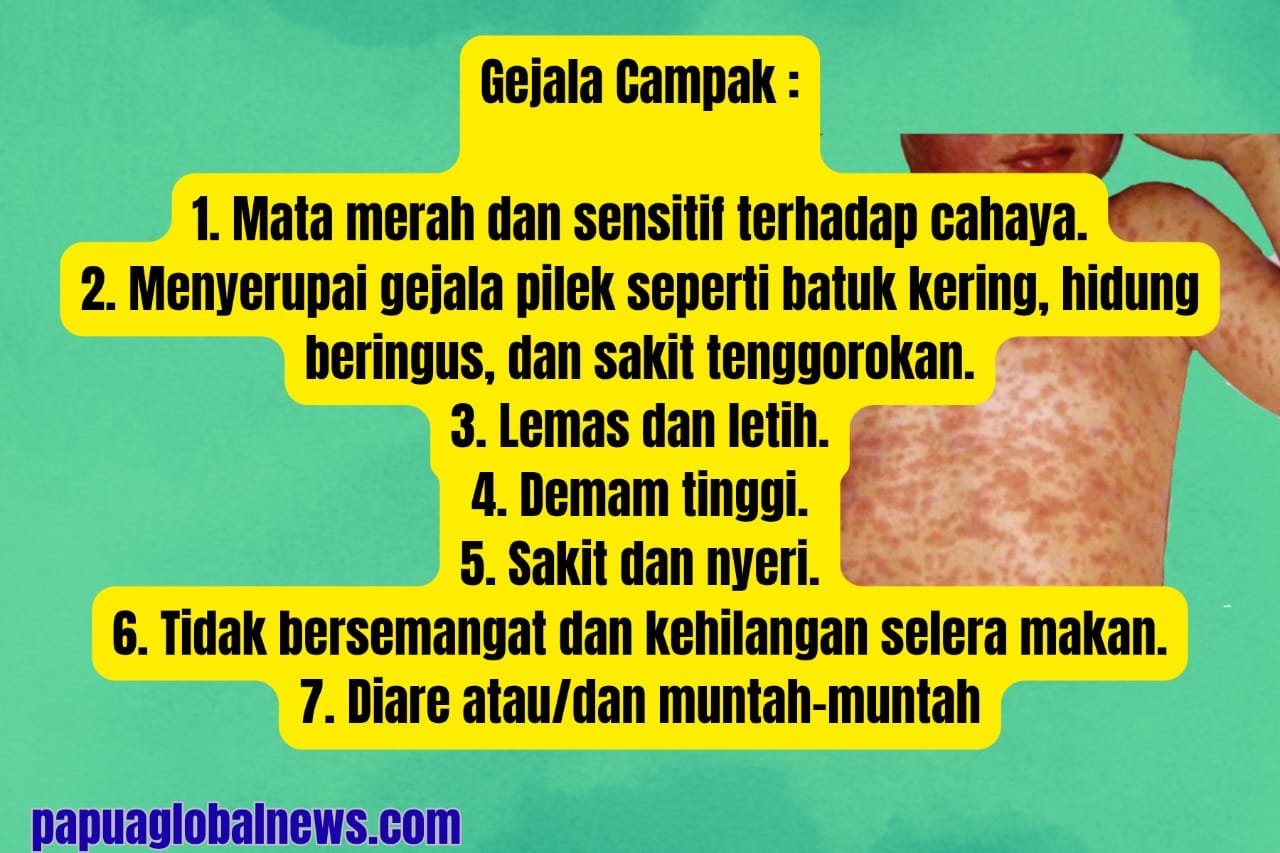APBD-P Rp6,8 Triliun: Keadilan Sosial yang Dipertaruhkan di Mimika
Oleh : Laurens Minipko
DPRK Mimika baru saja mengesahkan APBD Perubahan sebesar Rp6,8 triliun. Angka ini tampak fantastis, bahkan melebihi anggaran beberapa provinsi lain di Indonesia. Menariknya, angka sebesar itu menganga di depan realitas sosial masyarakat OAP yang masih kesulitan air bersih, fasilitas kesehatan terbatas, pendidikan yang timpang, transportasi yang belum merata, pengangguran kaum muda yang masih menghiasi keseharian, migrasi non-OAP yang mengemukan setiap waktu, konflik agraria yang menjamur, dll.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah APBD-P sebesar itu benar-benar akan menghadirkan keadilan sosial, atau hanya mempertebal jurang ketimpangan? Di sinilah kita bisa mengingat prinsip dasar konstitusi Indonesia: “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bukan sebatas slogan, melainkan ukuran keberhasilan kebijakan anggaran.
APBD-P sebagai Medan Kuasa
APBD-P sering dilihat hanya sebatas catatan angka, padahal ia merupakan medan kuasa dengan muatan sosial, moral dan etika. Michel Foucault (1975) dalam Discipline and Punish menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui represi, tetapi juga melalui regulasi, kebijakan, dan mekanisme administratif yang tampak netral. Dengan kata lain, anggaran adalah instrument kuasa: ia mengatur siapa yang mendapat manfaat, dan siapa yang tersisih, atau dikorbankan.
Dalam konteks Mimika, APBD Rp6,8 triliun menjadi arena perebutan kepentingan: pemerintah daerah ingin mengukuhkan legitimasi politiknya, elit DPRK mencari ruang tawar, kontraktor berburu proyek, sementara rakyat kecil berharap ada kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Kuasa anggaran ini ibarat pisau bermata dua: bisa menjadi instrument keadilan, tapi bisa juga berubah menjadi alat dominasi.
Dimensi Keadilan Sosial dalam APBD
APBD-P bukan sebatas dokumen anggaran, melainkan cermin keadilan sosial di daerah. Ia memuat pilihan politik: siapa yang diutamakan, siapa yang disisihkan, serta nilai apa yang dianggap penting untuk masa depan Bersama. Di Mimika, APBD dimimpikan menjawab kesenjangan sosial, memastikan kelompok rentan tidak tertinggal, dan memberi ruang partisipasi masyarakat, bukan medan transaksional. Oleh karena itu penting menakar APBD-P melalui tiga wajah keadilan berikut:
1. Keadilan Distributif
Aristoteles dalam Nicomachean Ethics menekankan keadilan distributif: memberikan sesuai dengan kebutuhan dan proporsi. John Rawls (1971) menambahkan prinsip “difference principle”, yakni ketimpangan hanya bisa dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling lemah.
Untuk membantu kita mencermati implementasi APBD-P Mimika 2025, berikut pertanyaan-pertanyaan kritis:
1. Apakah alokasi anggaran APBD-P Mimika sudah mencerminkan kebutuhan riil masyarakat kecil, bukan hanya kepentingan elite politik dan elite birokrasi?
2. Sejauh mana APBD-P mengutamakan belanja publik (Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi rakyat) dibanding belanja birokrasi?
3. Bagaimana mekanisme APBD-P mengatasi ketimpangan antar wilayah dalam Kabupaten Mimika (kota vs kampung, pesisir vs pegunungan).
4. Apakah dana Otsus dan transferan pusat benar-benar diarahkan untuk memperbaiki ketidakadilan historis terhadap orang asli Papua?
5. Siapa yang paling diuntungkan dari APBD-P Mimika, dan siapa yang paling dirugikan?
2. Keadilan Prosedural
Amartya Sen (2009) dalam The Ideal of Justice menegaskan pentingnya proses yang adil, bukan hanya hasil. Proses penyusunan APBD-P seharusnya transparan dan partisipatif (dekat dengan mata rakyat).
Pertanyaan-pertanyaan kritis yang dapat dipakai untuk mencermati aspek keadilan ini:
1. Apakah proses penyusunan APBD-P sudah partisipatif, melibatkan suara masyarakat akar rumput? Apakah Musrenbang sudah merepresentasikan suara akar rumput?
2. Bagaimana DPRK Mimika mengawasi dan menimbang aspirasi mayarakat dalam pembahasan APBD, ataukah mereka hanya menyetujui rancangan eksekutif tanpa kritik?
3. Apakah mekanisme transparansi (public rancangan, realisasi, dan laporan keuangan APBD) mudah diakses masyarakat?
4. Bagaimana ruang kontrol masyarakat sipil, media, dan akademisi dalam megawasi jalannya penyusunan APBD-P dan implementasinya?
3. Keadilan Substantif
Menurut konsep Substantif justice, ukuran akhir keadilan adalah sejauh mana rakyat benar-benar merasakan manfaat.
Kita dapat bertanya dengan kritis aspek keadilan substantif:
1. Apakah realisasi APBD-P Mimika telah mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial di daerah ini?
2. Bagaimana mengukur keberhasilan APBD-P dalam menjawab kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur kampung?
3. Apakah APBD-P mampu menciptakan lapangan kerja dan ruang ekonomi baru bagi mama-mama Papua, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, baik OAP maupun non-OAP?
4. Bagaimana memastikan agar dana pembangunan tidak tersedot ke proyek mercusuar yang minim manfaat sosial?
5. Apakah APBD-P benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, atau hanya sebatas instrument politik dan birokrasi?
6. Bagaimana kita bisa menilai APBD-P bukan hanya dari sisi legal-formal, tetapi dari moralitas keadilan untuk semua warga Mimika?
Ontologi Pengawasan
Fraksi PDI-P dalam sidang DPRK Mimika menyatakan akan melakukan “pengawasan ketat” terhadap jalannya APBD-P Rp6,8 triliun. Namun, pertanyaan kritisnya: apa makna pengawasan itu?
Pengawasan adalah jantung dari tata kelola keuangan daerah, termasuk APBD-P. Ada pihak yang diberi wewenang mengawasi: DPRK yang mengawasi eksekutif, ada BPK yang memeriksa, ada Inspektorat yang memantau internal.
Apakah pengawasan dilakukan terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil, ataukah hanya sebatas retorika politik untuk memperkuat posisi tawar fraksi? Pertanyaan tajam pun muncul: “Quis custodiet Ipsos custodes?” (siapa yang mengawasi para pengawas?), sebuah pertanyaan klasik dari filsuf Romawi, Juvenal, yang tetap relevan hingga hari kini. Ketika pengawas punya kuasa, siapa yang memastikan bahwa kuasa itu dijalankan dan tidak disalahgunakan? Di sinilah letak paradoks fungsi pengawasan itu. Dalam perspektif filosofis itu, rakyat adalah pengawas sejati bagi para pengawas. Mengapa? Karena kepentingan rakyat yakni keadilan sosial adalah roh dari kebijakan anggaran dalam wujud APBD-P.
Mimikia dan Luka Ekstraktif
Mimika adalah wilayah kaya secara kasat mata. Di sinilah berdiri tambang emas raksasa dunia, PT Freeport Indonesia. Ironisnya, di tengah limpahan sumber daya, masyarakat asli Kamoro dan Amungme justru masih berhadapan dengan kemiskinan struktural, kehilangan ruang hidup, dan minim akses terhadap kesejahteraan.
Teori David Harvey (2003) tentang accumulatin by dispossession menjelaskan fenomena ini: akumulasi kekayaan lahir dari perampasan tanah, sumber daya, dan ruang hidup masyarakat adat. Dalam konteks ini, APBD seharusnya hadir sebagai instrumen redistribusi keadilan, untuk menutup luka ekstraktif yang sudah lama diderita rakyat Mimika.
APBD-P sebagai Ruang Pertaruhan
Pada akhirnya, APBD Mimika bukan sebatas dokumen fiskal, melainkan ruang pertaruhan keadilan sosial. Dengan nilai Rp6,8 triliun, ada dua jalan yang mungkin ditempuh:
1. Jika salah kelola, APBD-P hanya akan memperkuat elite, memanjakan birokrasi, dan melanggengkan ketimpangan.
2. Jika benar dikelola, ia bisa menjadi jembatan rekonsiliasi sosial-ekonomi, menghadirkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi rakyat Mimika, terutama masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.
Keadilan sosial bukan hanya retorika dalam konstitusi, melainkan tanggung jawab nyata. APBD-P Rp6,8 triliun di Mimika adalah ujian: apakah negara benar-benar hadir untuk rakyat, atau malah memperpanjang dominasi kuasa di atas penderitaan mereka. (Isi tulisan tanggung jawab penulis)