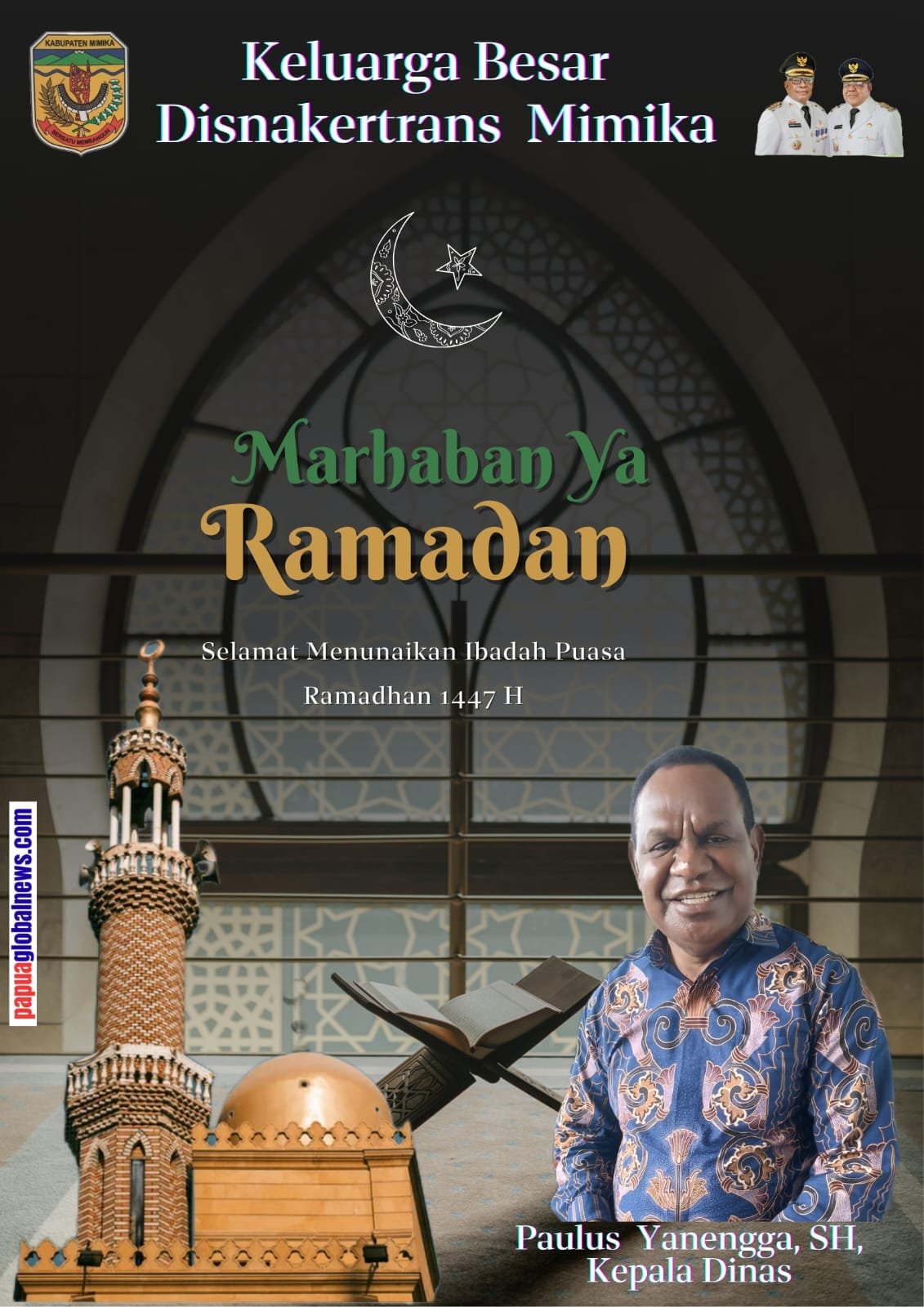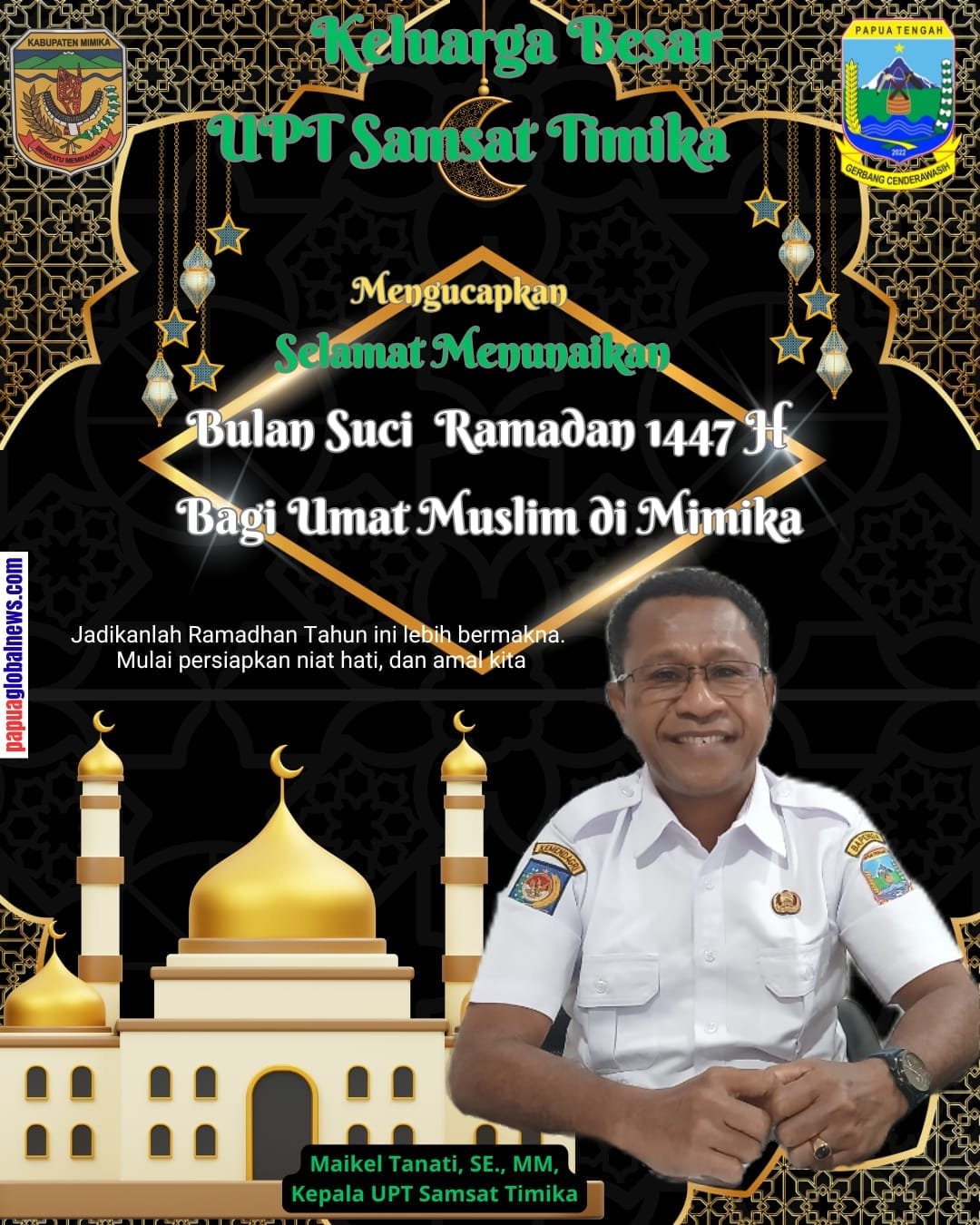Ontologi Fransiskan Sebagai Kritik atas PSN dan Ekstraksi Tambang di Papua
Di Papua, logika ini terlihat jelas. Masyarakat adat sering kali diposisikan sebagai hambatan regulatif, bukan subjek makna. Tanah adat menjadi “area terdampak”. Kehidupan kultural menjadi “variabel sosial”. Di sinilah ontologi Fransiskan berfungsi sebagai kritik diam-diam yang radikal. Dan, jika hidup tidak bisa direduksi menjadi objek hukum dan pasar, maka seluruh arsitektur kehilangan legitimasi ontologisnya.
Fransiskan tidak menyerang negara. Ia membuat negara dan otoritas lainnhya kehilangan dasar moralnya.
Inoperativitas: Politik Tanpa Merebut Kekuasaan
Agamben menyebut bentuk hidup Fransiskan sebagai inoperativitas. Sebuah cara hidup yang membuat mesin kekuasaan kehilangan objek kerjanya. Bayangkan jika relasi terhadap tanah tidak lagi berbabsis kepemilikan, melainkan berbasis persekutuan. Bayangkan jika pembangunan tidak lagi dimulai dari konsesi, melainkan dari keberlangsungan komunitas.
Ontologi Fransiska tidak mengajak kita membakar tambang. Ia mengajak kita mempertanyakan: mengapa kita merasa harus memilikinya? Ini bukan perlawanan frontal. Ini pembatalan cara berpikir.
Papua dan Spiritualitas Anti-Ekstraksi
Di banyak kampung Papua, relasi dengan tanah bukan relasi ekonomi semata. Ia adalah kosmologi. Ia adalah memori luhur. Ia adalah tubuh kolektif. Nah, Ontologi Fransiskan menemukan resonansinya di sini.
Ketika mama-mama di pasar menjual pinang bukan untuk akumulasi, tetapi untuk keberlangsungan hidup harian-itu bukan sebatas ekonomi kecil. Itu bentuk hidup.
Ketika orang di Intan Jaya mempertahankan hutan bukan demi karbon kredit, tetapi demi keseimbangan kosmos-itu bukan romantisme. Itu ontologi. Dan justru karena itu, ekstraksi besar terasa seperti pelanggaran metafisik, bukan hanya ekologis.
Pertanyaan yang Tidak Aman dan Jalan Ketiga
Apakah negara berhak menyebut tanah sebagai “strategis” tanpa bertanya pada mereka yang hidup di dalamnya? Apakah pembangunan selalu identik dengan percepatan industri? Apakah kemiskinan selalu harus diselesaikan melalui eksploitasi sumber daya? Atau mungkin, seperti Fransiskan, kita perlu belajar bahwa hidup bisa bermakna tanpa kepemilikan absolut?
Di tengah polarisasi antara anti-pembangunan dan pro-investasi, ontologi Fransiskan menawarkan jalan ketiga. Bukan nihilisme. Bukan fanatisme. Tetapi kesetiaan pada kehidupan sebagai relasi.
Jika PSN mengandaikan bahwa masa depan Papua ada di dalam perut bumi, maka ontologi Fransiskan mengingatkan: masa depan mungkin justru ada pada cara kita hidup di atasnya. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukanlah “berapa ton emas yang tersimpan?” melainkan “apa arti hidup jika semuanya menjadi tambang?” **