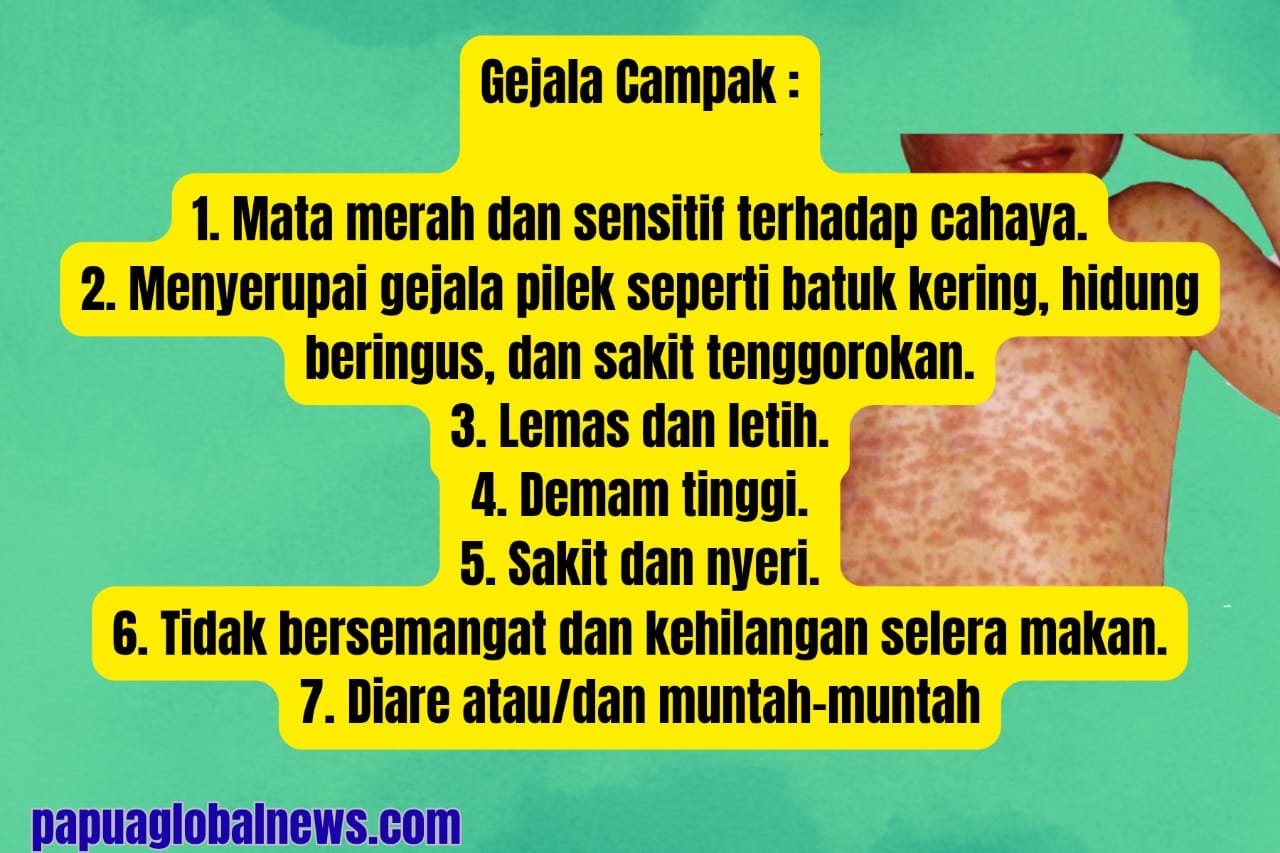Kita Makan Sagu, Bukan Minum Minyak
Oleh : Laurens Minipko
“Kita makan sagu, bukan minum minyak.” Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan jenaka. Namun di situlah letak daya kritiknya. Ia menyingkap jurang antara logika negara-pasar dan logika hidup orang Papua (antara imajinasi pembangunan dari atas dan realitas tubuh, tanah, serta pangan lokal dari bawah).
Dalam kerangka politik ekologi kritis, pembangunan tidak pernah netral. Seperti ditegaskan David Harvey, kapitalisme bekerja melalui accumulation by dispossession: tanah dan sumber daya diambil alih atas nama kepentingan publik, lalu dimasukkan ke dalam sirkuit modal. Di Papua, logika ini tampil telanjang. Tanah tidak lagi dibaca sebagai ruang hidup, melainkan sebagai aset strategis pangan dan energi nasional.
Sagu, bagi orang Papua, bukan sekadar karbohidrat. Ia adalah arsip ekologis, identitas kultural, dan etika hidup. Sagu tumbuh tanpa memaksa tanah bekerja secara eksploitatif. Ia menopang relasi manusia dengan alam yang berumur ratusan tahun. Dalam sagu, tubuh belajar tentang cukup, bukan tentang akumulasi. Karena itu, mengganti sagu dengan sawit bukan sekadar pergantian komoditas, melainkan pergeseran cara hidup: dari hidup bersama alam menuju hidup untuk pasar.
Logika inilah yang muncul berulang dalam proyek-proyek besar negara seperti MIFEE, Proyek Strategi Nasional (PSN), dan belakangan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Ketiganya berbagi asumsi yang sama: Papua adalah ruang strategis yang sah direkayasa dari atas. Tanah adat dipetakan ulang sebagai koridor investasi, hutan dan rawa diposisikan sebagai cadangan pangan dan energi nasional. Tanah bekerja, tetapi nilai berangkat pergi.
Imajinasi ini ditegaskan secara terbuka dalam pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa 16 Desember 2025. Hadir seluruh gubernur dari enam provinsi, 42 bupati dan wali kota, serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Presiden menekankan percapatan pembangunan, pengamanan kekayaan negara, serta penguatan swasembada pangan dan energi hingga ke tingkat daerah. Papua disiapkan sebagai kawasan strategis kemandirian energi nasional, disertai janji pembangunan rumah sakit, sekolah, pariwisata, keamanan dan infrastruktur.
Sekilas, pesan ini terdengar menjanjikan. Namun persoalannya terletak pada kerangka besarnya. Papua kembali dibayangkan terutama sebagai ruang strategis negara dan korporasi, bukan sebagai ruang hidup masyarakat adat. Swasembada didefinisikan dari atas melalui proyek besar (sawit, jagung, dst), bukan dari bawah melalui pangan lokal seperti sagu.
Kontradiksi itu tampak jelas ketika Gubernur Papua Tengah, selaku Ketua Perhimpunan Gubernur se-Tanah Papua, menyampaikan keberatan terbuka di hadapan Menteri Dalam Negeri. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak akan berjalan jika Dana Otonomi Khusus terus dipangkas. “Apa yang kita bicarakan hari ini tidak akan jalan. Dana Otsus sudah dipangkas…” Ia mendesak agar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 direview, karena pemangkasan Otsus bertolak belakang dengan retorika percepatan.
Di sinilah paradoks pembangunan Papua menjadi terang: negara mendorong perepatan, swasembada, dan proyek strategis, tetapi instrumen utama yang menopang layanan publik dan kehidupan sehari-hari justru dilemahkan. Papua diminta berlari, sementara alas kakinya dilepas.
Situasi ini memperlihatkan apa yang dapat disebut sebagai kapitalisme berwajah amanah. Kapitaslisme tidak hadir dengan wajah kasar, melainkan dibungkus bahasa moral: kedaulatan energi, kepentingan nasional, dan pengabdian kepada rakyat. Negara tampak netral dan peduli, padahal sedang menyiapkan ruang politik dan ekologis bagi akumulasi modal.
Dalam konteks ini, posisi bupati dan gubernur di Papua menjadi sangat dilematis. Di satu sisi, mereka dipilih oleh rakyat yang hidup dari sagu, hutan, dan tanah adat. Di sisi lain, mereka diikat oleh arahan pusat, target pembangunan, dan disiplin proyek nasional. Meminjam Antonio Gramsci, kepala daerah berada di antara dua hegemoni: hegemoni negara-kapital dan hegemoni lokal rakyat. Ketika mereka tunduk sepenuhnya pada arahan pusat, mereka tidak sedang netral, mereka sedang memihak.
Otonomi daerah seharusnya memberi ruang bagi kepala daerah untuk menafsir, bahkan mengoreksi kebijakan pusat ketika bertabrakan dengan ekologi dan martabat hidup masyarakat adat. Tanpa keberanian etik itu, jabatan kepala daerah berisiko direduksi menjadi fungsi administratif belaka.
“Kita makan sagu, bukan minum minyak” pada akhirnya bukan sekadar slogan. Ia adalah pernyataan politis dan etis tentang apa yang layak dijadikan dasar pembangunan. Selama Papua terus dibaca sebagai ladang energi dan proyek strategis, sementara pangan lokal dan ruang hidup masyarakat adat dipinggirkan, maka pembangunan akan terus kehilangan maknanya.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat membangun proyek, tetapi bangsa yang tahu apa yang pantas dimakan rakyat, siapa yang harus didengar, dan tanah mana yang tidak boleh dikorbankan atas nama apa pun. **