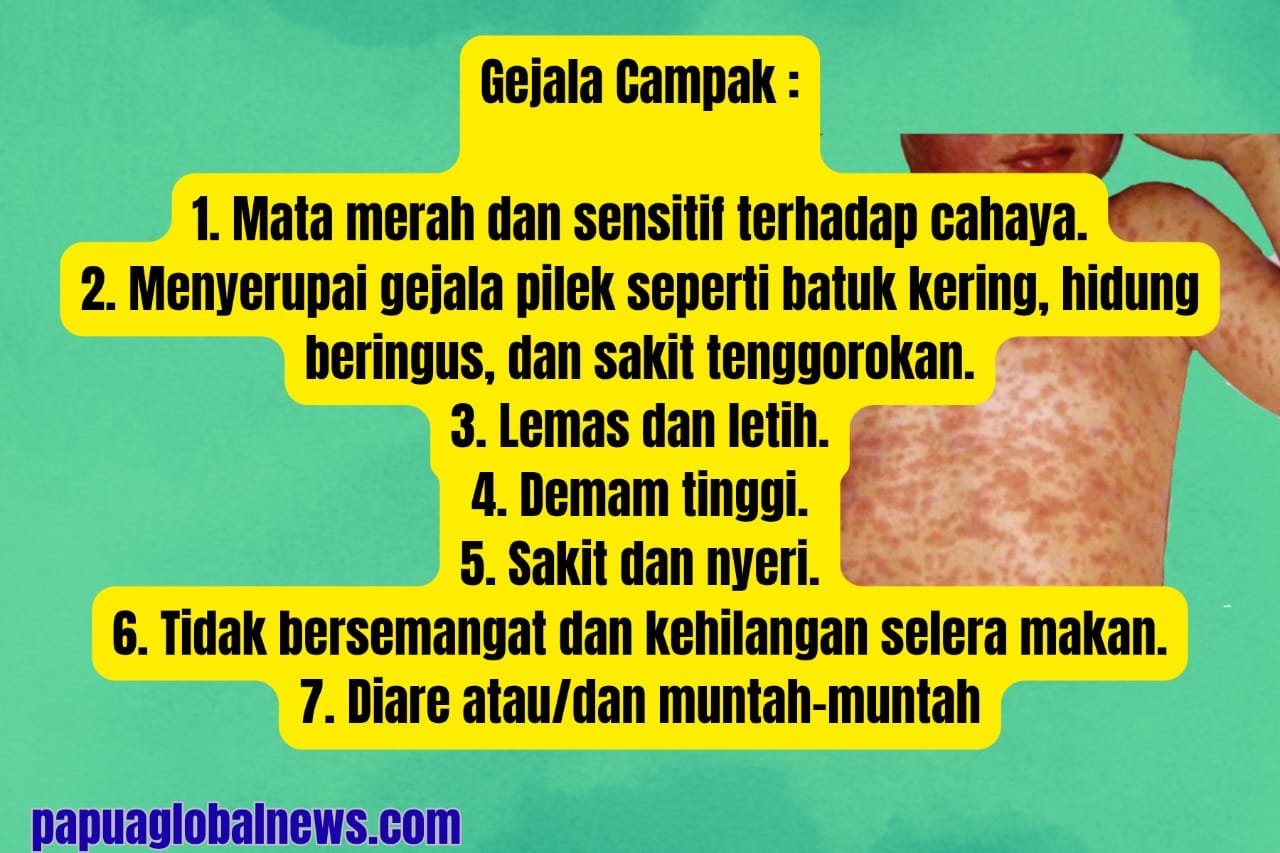Ketika Bhinneka Tunggal Ika Kehilangan Makna: Rasisme dan Intoleransi Merusak Fondasi Moral Bangsa
Oleh: Johanes Eliezer Samsong Wato – Mahasiswa Doktoral di Bonn International Graduate School-Oriental and Asian Studies (BIGS-OAS), University of Bonn.
TULISAN ini menyoroti krisis pluralisme yang tengah mengguncang Indonesia. Rasisme, intoleransi, dan kebencian berbasis identitas merasuki ruang publik, pendidikan, dan olahraga, mengikis makna Bhinneka Tunggal Ika. Kasus rasisme terhadap orang Papua, ujaran kebencian di media sosial, hingga sikap diskriminatif guru menjadi cermin kegagalan moral dan pendidikan bangsa. Penulis menekankan bahwa pluralisme bukan sekadar hafalan dalam buku Pancasila, tetapi nilai hidup yang harus diterapkan melalui pendidikan karakter, pelatihan guru beretika, dan ruang dialog antarbudaya. Artikel ini merupakan panggilan moral bagi negara, guru, dan masyarakat: Membangun kembali jiwa republik melalui kesadaran, empati, dan penghormatan terhadap kemanusiaan setiap warga. Keberhasilan menanamkan pluralisme akan menjadi pesan moral bagi dunia, kegagalan akan menandai kemunduran bangsa.
Selama puluhan tahun, dunia memandang Indonesia sebagai laboratorium hidup dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika – “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Negeri ini dibangun di atas keberagaman: Ratusan etnis, agama, dan bahasa bersatu dalam satu rumah besar bernama republik. Namun hari ini, fondasi kebangsaan itu retak. Rasisme, intoleransi, dan kebencian berbasis identitas menjalar dari ruang maya ke ruang nyata, dari pasar hingga ruang kelas, dari stadion hingga kantor pemerintahan. Semboyan kebinekaan kian sering hanya menjadi hiasan pidato kenegaraan, bukan lagi napas kehidupan sosial bangsa.
Rasisme yang Menjadi Luka Nasional
Kasus rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP) menjadi cermin paling menyakitkan dari kegagalan kita memahami kemanusiaan. Peristiwa Surabaya 2019, ketika mahasiswa Papua dihina dan disebut dengan kata-kata rasial oleh aparat dan Ormas, seharusnya menjadi peringatan nasional. Namun luka itu tak kunjung sembuh. Setiap tahun, bentuk-bentuk baru diskriminasi bermunculan: Ejekan, penghinaan, hingga stereotip yang menihilkan martabat manusia Papua.
Lebih menyedihkan lagi, rasisme kini merasuki dunia olahraga. Terkini, ketika Tim Nasional sepak bola Indonesia kalah di Piala Dunia, dua kakak beradik Sayuri, berdarah Papua yang menjadi pemain nasional Indonesia, menjadi sasaran ujaran rasis di media sosial Indonesia. Klub Persipura Jayapura, simbol kebanggaan masyarakat Papua, sering menerima ejekan bernada rasis dari suporter lawan. Ironisnya, hal yang paling menyedihkan adalah ketika guru-pilar moral bangsa-ikut melanggengkan rasisme. Dalam sebuah video viral, seorang guru di NTT tertangkap kamera sedang mengatakan bahwa “orang Papua makan tanah.”
Ucapan itu bukan sekadar candaan keliru, tetapi cermin kegagalan mendasar dari seorang pendidik. Jika para guru, pilar moral dan intelektual bangsa sudah menormalisasi pelecehan rasial, apa yang bisa kita harapkan dari generasi muda yang mereka bentuk?
Krisis Moral Dibalik Pluralisme yang Palsu
Indonesia tidak kekurangan semboyan kebangsaan, melainkan keteladanan moral. Pluralisme terlalu sering diajarkan sebagai konsep hafalan dalam buku Pancasila, tetapi jarang dihidupkan sebagai nilai yang dijalani. Anak-anak di sekolah diajari bahwa Indonesia itu “beragam”, tapi tidak dilatih untuk benar-benar hidup bersama dalam keberagaman itu.
Kita telah gagal menjadikan pendidikan sebagai arena pembentukan empati. Kurikulum penuh nilai, tetapi kosong dari pengalaman kemanusiaan. Para siswa diajari doktrin, bukan dialog; diingatkan untuk patuh, bukan berpikir kritis; dibiasakan seragam, bukan menghargai perbedaan.