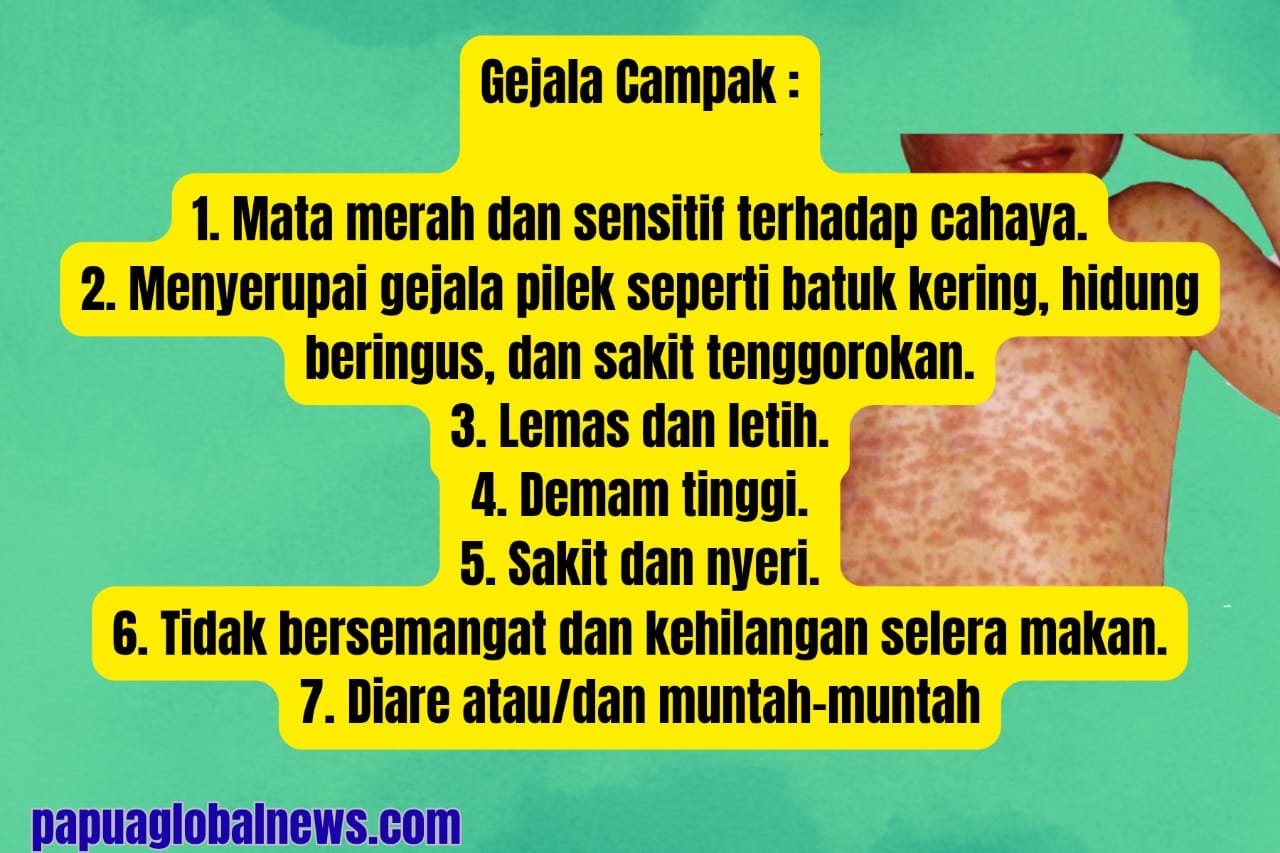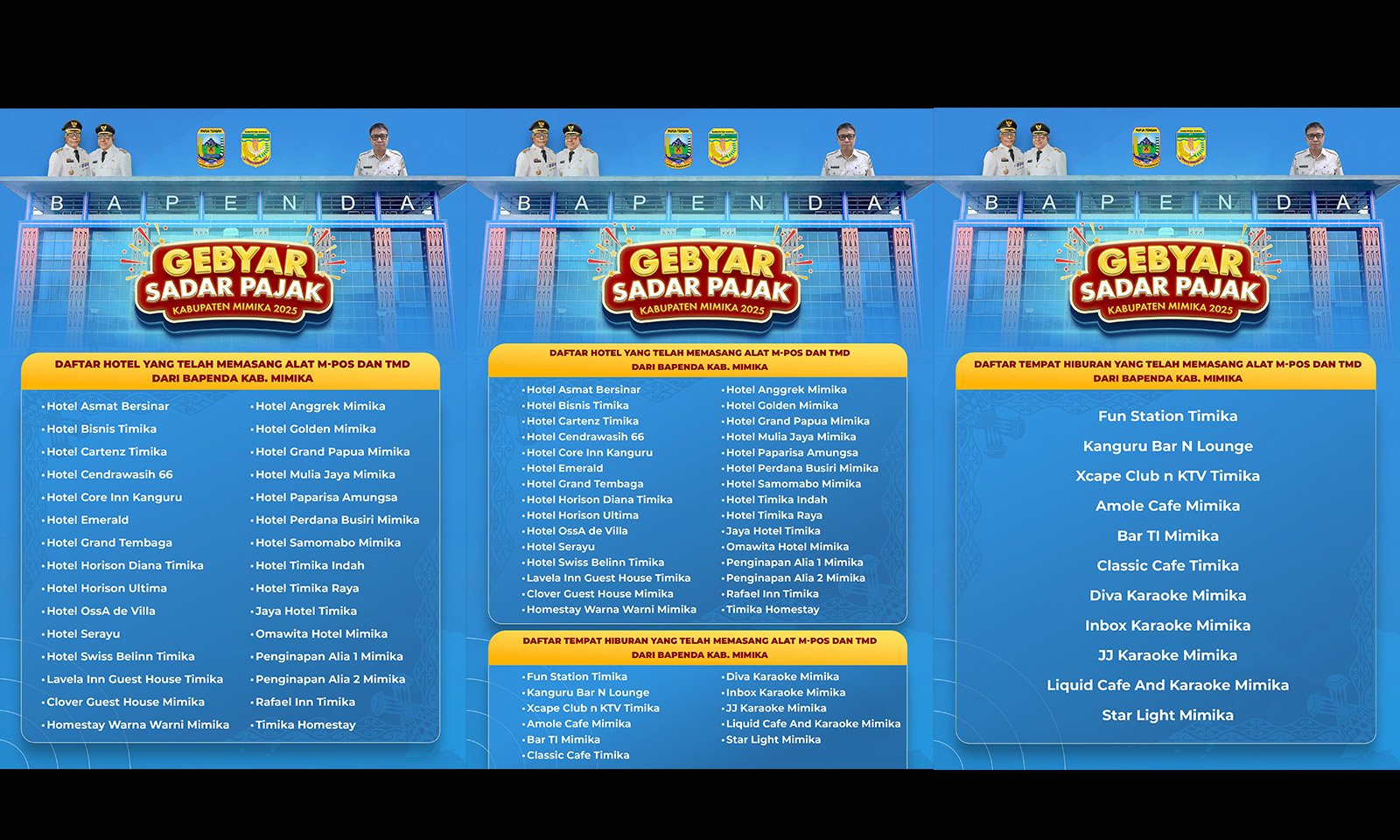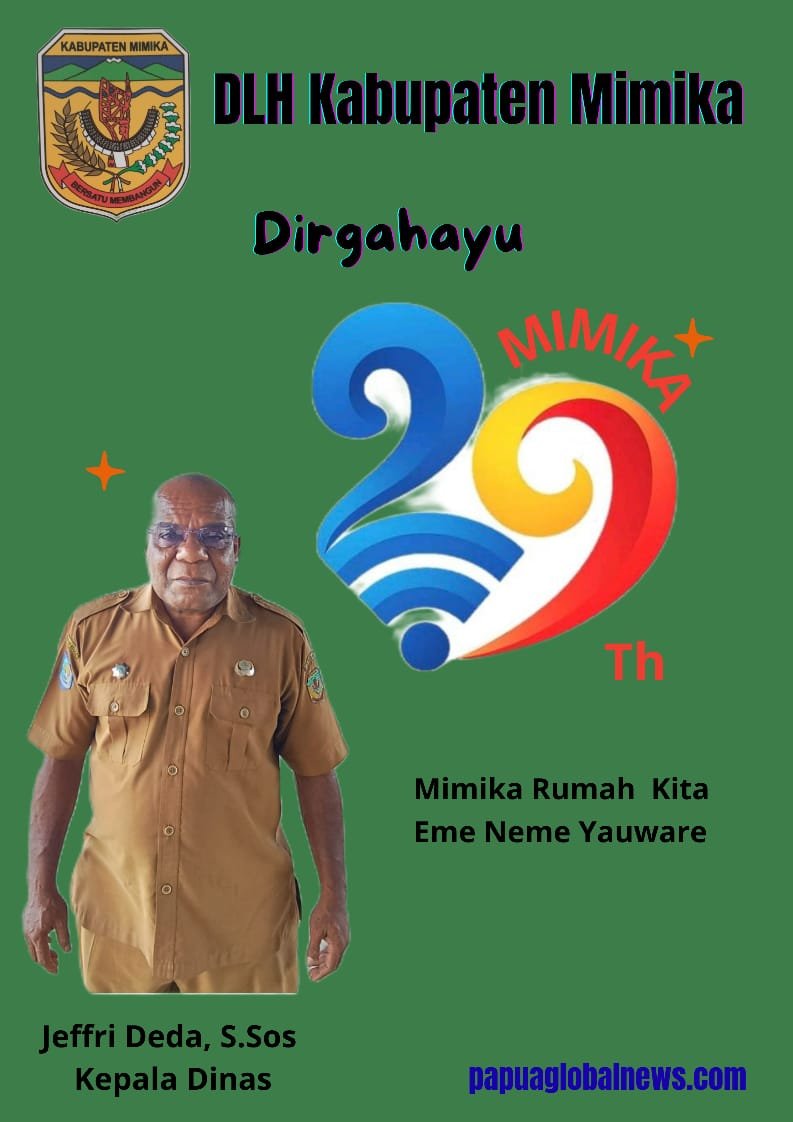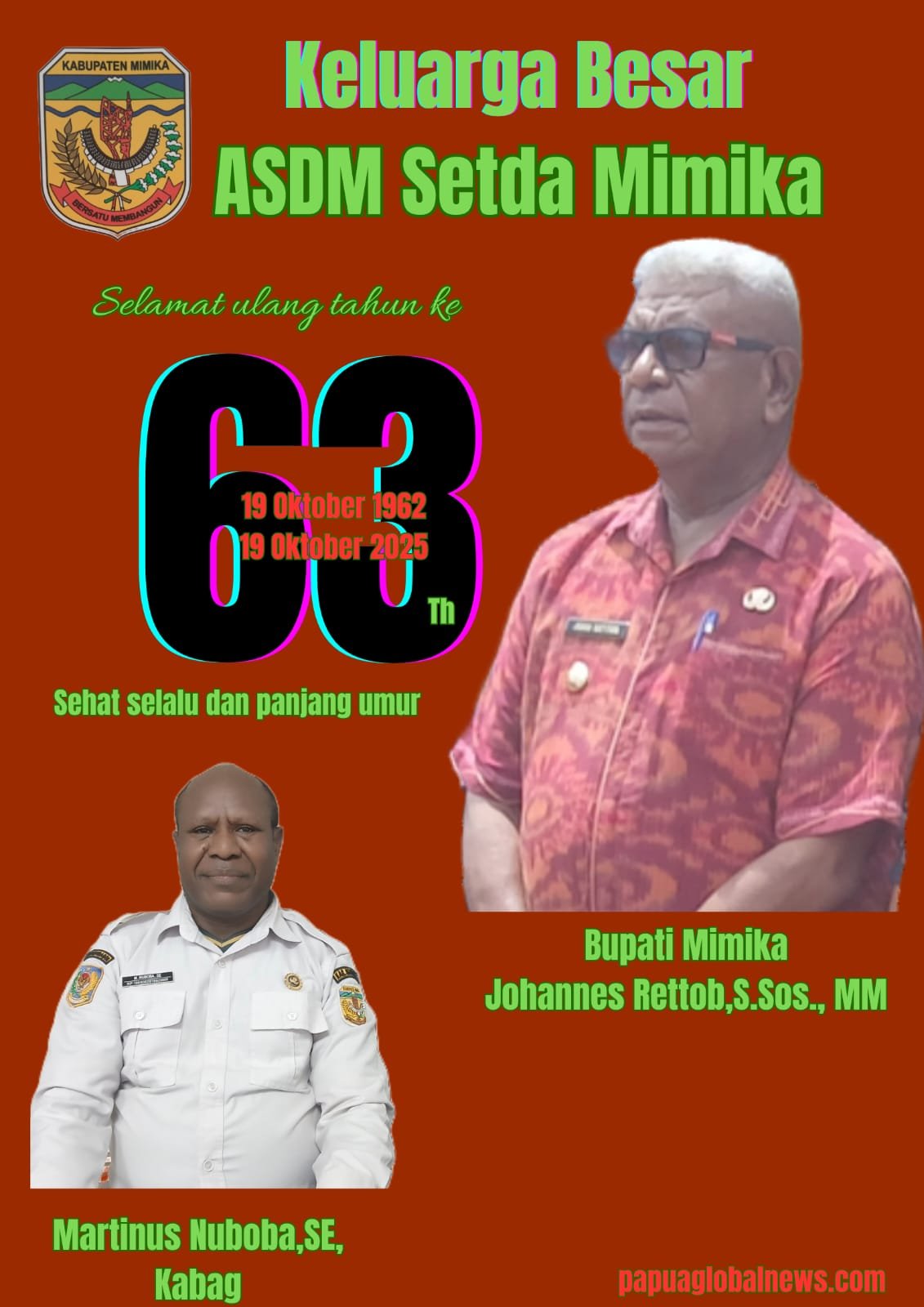Antara Harapan dan Pengulangan: Masyarakat Papua di Tengah PSU Gubernur
Oleh : Laurens Minipko
“Harapan adalah tindakan politis. Ia bukan sekadar menunggu, tapi berani merancang kemungkinan di tengah ketidakpastian” (Paul Freire)
PENGULANGAN pemungutan suara atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk posisi Gubernur Papua periode 2025-2030 bukan sekadar teknis elektoral. Ia adalah momen politis yang membuka ruang refleksi atas apa yang tidak selesai, apa yang terus diulang, dan apa yang mesti dibayangkan ulang.
PSU Pintu Gerbang Refleksi Kritis
PSU adalah momen politis yang membuka ruang refleksi atas apa yang tidak selesai. Ia wujud dari event politis yang abnormal. Mengapa?? Karena ia bukanlah bagian normal dari siklus demokrasi, melainkan tanda keretakan, sengketa, atau anomali dalam proses elektoral. Ia membuka “ruang krisis” yang sejatinya menguak cacat sistemik, bukan sekadar salah teknis.
PSU ini bukan saja jedah administratif, tapi momen kontemplatif. Masyarakat, penyelenggara, dan elite politik dipaksa menoleh ke belakang dan bertanya. Apa yang gagal kita bangun bersama sebagai fondasi demokrasi lokal?? Refleksi menjadi peluang untuk mengurai ulang soal partisipasi, keadilan politik, relasi pusat-daerah, dan kekuasaan informal (Ormas, aparat, premanisme, dll).
Apa yang tidak selesai?? Kalimat ini menyimpan kritik mendalam. Bahwa Papua hidup dalam akumulasi “penundaan sejarah”. PSU hanya gejala dari penyakit lebih dalam:
• Sistem perwakilan yang timpang.
• Politik uang dan kekerasan.
• Sentralisasi keputusan.
• Fragmentasi sosial akibat desain kekuasaan yang eksklusif.
Dalam perspektif ini (hermeneutika kritis), PSU bisa dibacara sebagai momen peristiwa yang mengungkap kebenaran tersembunyi. Ia seperti tetes air terakhir yang meluberkan gelas penuh konflik diam-diam.
PSU sebagai event politis yang abnormal. Ia bukanlah bagian normal dari siklus demokrasi, melainkan tanda keretakan, sengketa, atau anomali dalam proses elektoral. Ia membuka ruang krisis yang sejatinya menguak cacat sistemik, bukan sekadar salah teknis.
Jika PSU hanya dimaknai sebagai perbaikan prosedur, maka kita sedang menutup mata terhadap luka dan aspirasi yang lebih dalam dari rakyat Papua.