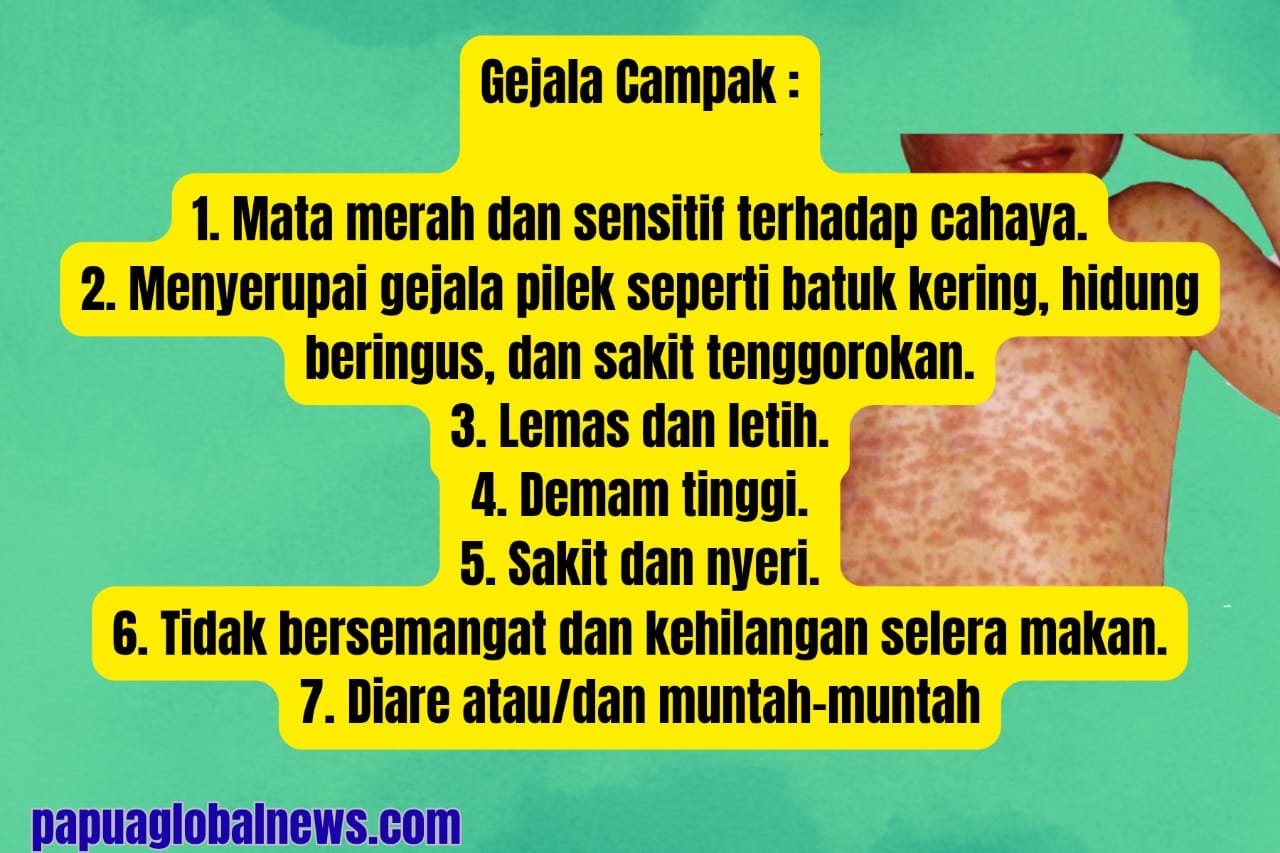Luka Dualisme Lemasko dan Jalan Pengobatan
Oleh : Laurens Minipko
SABTU sore, 9 Agustus 2025, belasan lelaki berdiri rapat di sebuah halaman di Jalan Ahmad Yani, Timika. Di tengah mereka Gregorius Okoare, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko) berdiri dengan wajah tegas. Ia didampingi Marianus Maknaepeku, Wakil Ketua, serta tokoh pemuda Kamoro Jhon Mamiri. Kepalan tangan dan jempol terangkat dalam sesi foto singkat itu adalah pernyataan sikap: Lemasko pimpinan Gregorius menolak Musyawarah Adat Suku Kamoro (Musdat) yang direncanakan berlangsung September 2025 (Papuaglobalnews, Sabtu , 9 Agustus 2025).
Di balik momen singkat itu, tersembunyi kisah panjang tentang retaknya kesatuan lembaga adat yang mestinya menjadi simbol persatuan Suku Kamoro. Dualisme kepemimpinan Lemasko yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir kini berubah menjadi konflik internal yang berlapis. Adat, politik, dan ekonomi. Mengingat potret konflik tersebut, tulisan ini ditempatkan dalam cakrawala kajian politik, ekonomi dan antropologi.
Akar Sejarah Lemasko
Lemasko dibentuk pada awal 1996, lahir dari kebutuhan Suku Kamoro untuk memiliki wadah resmi yang diakui pemerintah dan perusahaan tambang raksasa yang beroperasi di Mimika. Fungsi utamanya adalah memperjuangkan hak ulayat, melestarikan budaya, serta memastikan masyarakat Kamoro mendapat manfaat dari janji yang bernama pembangunan.
Struktur Lemasko mengadopsi prinsip musyawarah adat yang dipadukan dengan format organisasi modern. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bidang-bidang kerja. Dalam teori, Lembaga ini mewakili suara kolektif seluruh warga Kamoro, dari pesisir yang terbentang dari Barat ke Timur, hingga pedalaman Sungai (semisal Sempan).
Namun, sejak awal, Lemasko berdiri di persimpangan antara mandat adat dan intervensi eksternal. Sumber dana besar yang mengalir lewat program kemitraan perusahaan tambang dan bantuan pemerintah menjadi pisau bermata dua: membuka peluang pembangunan, tetapi juga menanam bibit perebutan pengaruh.
Munculnya Dualisme
Retakan pertama mulai terlihat ketika perbedaan tafsir mandat kepemimpinan tidak terselesaikan dalam Badan Musyawarah Adat (2010-2013) pasca kejadian itu. Dinamika dualisme itu muncul terus-menerus (2016, 2022, 2023, 2024, dan 2025). Ada yang menganggap pemilihan harus mengikuti garis marga tertentu sesuai adat, ada pula yang menekankan prosedur demokratis lewat pemungutan suara perwakilan kampung (Antara News, 15 Mei 2020).
Situasi memburuk ketika faksi berbeda mengklaim kepemimpinan sah. Dalam kasus terkini, kubu Gregorius Okoare menolak Musdat September 2025 yang digagas oleh kelompok lain yang disebut-sebut sebagai “kepemimpinan tidak sah” (Seputarpapua.com, Rabu 30 April 2025).
Kedua pihak sama-sama mengklaim legitimasi. Di mata kubu Gregorius, Musdat yang direncanakan itu tidak memenuhi prosedur adat, bahkan dianggap sarat intervensi politik dari pihak luar. Sementara faksi lawan berpendapat bahwa Musdat adalah jalan demokratis untuk menyegarkan kepemimpinan Lemasko dan memperluas partisipasi.
Dampak di Lapangan
Dualisme Lemasko bukan sebatas perdebatan di ruang rapat. Di kampung-kampung, warga mulai “terbelah”. Ada kampung yang menolak menghadiri acara “adat” jika difasilitasi kubu lawan. Bantuan dan program kemitraan pun terhambat karena kedua kubu saling menggugat hak tanda tangan di dokumen resmi.
Bagi masyarakat Kamoro yang bergantung pada tanah, laut dan Sungai untuk hidup, konflik ini terasa seperti kehilangan kompas. Generasi muda Kamoro pun mulai mempertanyakan integritas lembaga adat yang selama ini diagungkan (KontenMimika, 1 Desember 2023).
Analisis: Adat, Kuasa, dan Modal Simbolik
Konflik Lemasko dapat dibaca melalui lensa teori sosial-politik dan antropologi. Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang menguasai sumber daya, tetapi juga tentang menguasai definisi. Siapa yang berhak bicara sebagai “wakil adat” dan apa yang dimaksud dengan “kepentingan Kamoro”.
Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai perebutan modal simbolik yaitu pengakuan adat, legitimasi moral, yang kerap menjadi pintu masuk untuk mengakses modal ekonomi dalam bentuk dana kemitraan atau kompensasi tanah dan kali yang tercemar.
Dualisme Lemasko menunjukkan bagaimana modal simbolik itu diperebutkan di arena yang dipengaruhi modal sosial (jaringan dukungan kampung) dan modal politik (relasi dengan pejabat daerah atau Perusahaan).
Dari perspektif antropologi politik, Lemasko dapat dibaca sebagai Institusi Hiubrid. Ia berada di persimpangan antara sistem adat Kamoro yang berbasis marga, garis keturunan, dan wilayah ulayat, dengan sistem organisasi modern berbentuk badan hukum. Dualisme lahir dari benturan dua logika legitimasi ini.
Kacamata Clifford Geerts memaknai fenomena dualisme Lemasko sebagai theatre state. Dalam budaya Kamoro, kekuatan pemimpin diukur dari kemampuannya memimpin ritual kolektif, seperti Karapao. Ketika Lemasko terbelah, kedua kubu memanfaatkan ritual ini sebagai panggung legitimasi.
Intervensi Eksternal
Sejarah konflik adat di Papua menunjukkan pola yang berulang. Ketika lembaga adat terpecah, posisi tawar mereka terhadap pihak luar melemah (Institutional Capture). Dalam konteks Mimika, perusahaan tambang dan pemerintah daerah menjadi pihak yang “diuntungkan” ketika suara Kamoro terbelah, karena tuntutan bisa dinegosiasikan dengan kubu yang lebih “kooperatif”.
Sejumlah pemerhati lokal mengingatkan bahwa ketidaksatuan Lemasko berpotensi membuat kesepakatan-kesepakatan penting, dari kompensasi tanah dan air hingga proyek infrastruktur ditandatangai tanpa persetujuan kolektif.
Jalan Keluar yang Diperlakukan
Konflik ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan:
- Musyawarah Adat Netral, dipimpin oleh tetua adat lintas kampung yang tidak terlibat langsung dalam kedua faksi, tanpa kehadiran pihak luar yang berkepentingan.
- Reformasi AD/ART Lemasko, memastikan mekanisme pergantian kepemimpinan jelas, akuntabel dan diterima semua marga.
- Transparansi Dana dan Program, meminimalkan ruang kecurigaan dan tuduhan penyalahgunaan kewenangan.
- Pendidikan Politik Adat untuk Generasi Muda, membangun kesadaran kritis agar regenerasi kepemimpinan tidak mewarisi konflik lama.
Lemasko lahir untuk mempersatukan, bukan memecah belah. Dualisme kini terjadi hanyalah cermin dari tarik menarik kepentingnan di tubuh Suku Kamoro yang sedang berhadapan dengan arus besar politik dan ekonomi di Mimika.
Jika tidak segera diselesaikan, konflik ini berisiko meninggalkan luka sosial yang dalam, memeperlemah kedaulatan adat, dan mereduksi Lemasko menjadi sekadar nama dalam dokumen, bukan lagi ‘ROH’ yang mengikat orang Kamoro sebagai satu tubuh. (Isi tulisan tanggungjawab penulis)