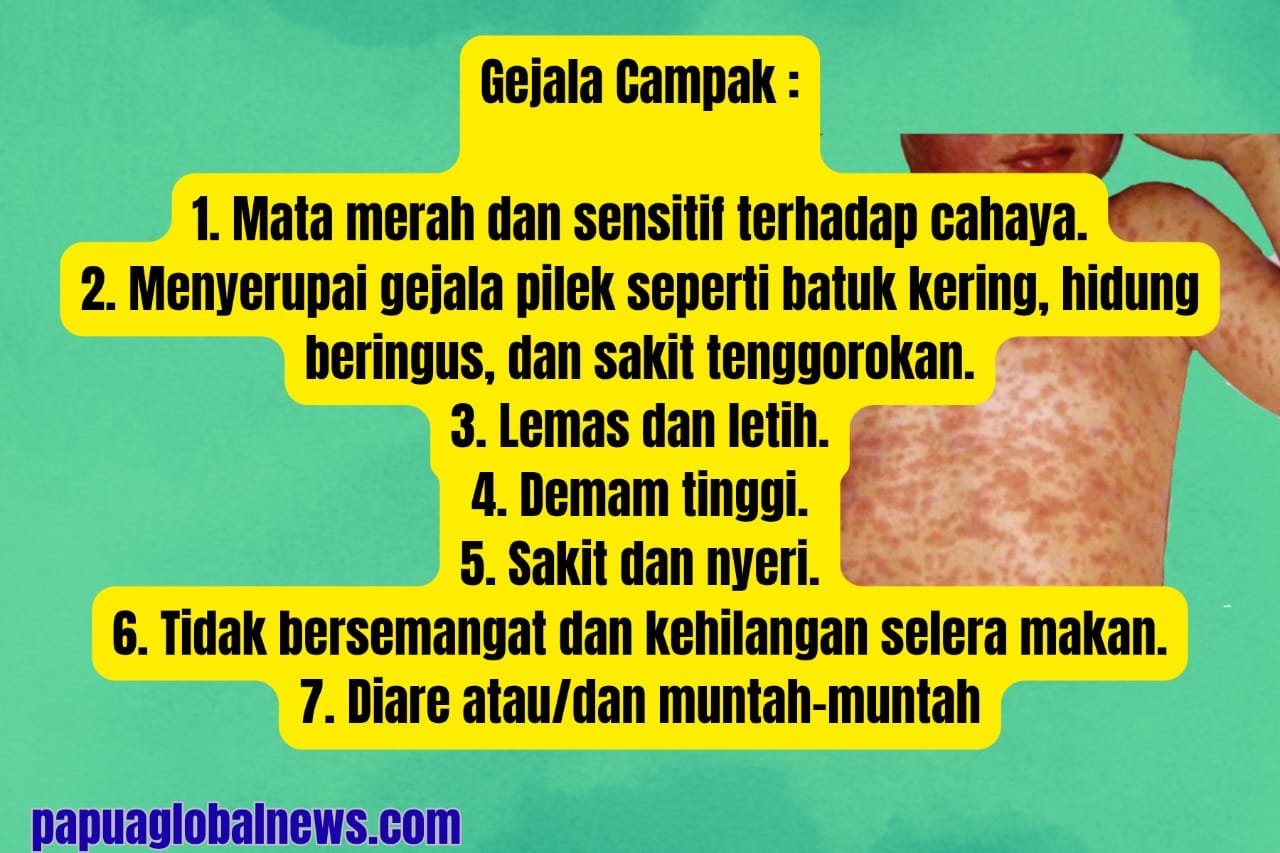Eme Neme Yauware vs Mimika Rumah Kita: Filosofi Masyarakat Adat yang Dipertaruhkan
Oleh: Johanes Eliezer Samsong Wato (Peneliti doktoral di Bonn International Graduate School – Oriental and Asian Studies (BIGS-OAS), University of Bonn, Jerman)
KABUPATEN Mimika, yang terletak di Papua, Indonesia, adalah wilayah yang kaya budaya dan sejarah, dengan dua suku besar pemilik hak ulayat, yakni Amungme dan Kamoro. Sejak berdirinya kabupaten ini, semboyan Eme Neme Yauware (ENY) telah menjadi simbol persatuan dan kekuatan kolektif masyarakat. Namun, belakangan muncul gagasan baru dari pemerintah daerah untuk memperkenalkan semboyan tambahan: Mimika Rumah Kita, sebuah frasa yang dianggap lebih inklusif dan mencerminkan semangat kebersamaan universal.
Gagasan ini memunculkan pro dan kontra, karena Eme Neme Yauware tidak hanya dipandang sebagai semboyan, tetapi juga sebagai filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang identitas, eksistensi budaya, dan arah pembangunan Kabupaten Mimika ke depan.
Apa jadinya jika sebuah rumah dibangun tanpa fondasi? Atau jika masyarakat tiba-tiba diminta mengganti akar identitasnya hanya karena alasan modernisasi? Inilah yang sedang terjadi di Kabupaten Mimika. Di balik jargon baru ‘Mimika Rumah Kita’, terselip kegelisahan mendalam: siapa yang berhak menentukan arah masa depan tanah ini, pemerintah, pendatang, atau masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah dan sejarahnya?
Eme Neme Yauware bukan sekadar semboyan tradisional. ia adalah filosofi hidup yang menuntun masyarakat Amungme dan Kamoro melewati masa-masa sulit berabad-abad. Maka, ketika jargon baru yang katanya lebih inklusif diperkenalkan, banyak yang bertanya: Apakah kita sedang membangun kebersamaan, atau justru menghapus jejak budaya lokal perlahan?
Di tengah deretan perusahaan tambang dan proyek industri besar, masyarakat adat Mimika justru semakin terpinggirkan. Bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena tidak diberi ruang menjadi subjek pembangunan. Sebelum bicara soul branding, tagline, atau kota cerdas, mari kita bertanya: Apa arti rumah bagi masyarakat adat, dan siapa yang sebenarnya membangunnya?
Tulisan ini mengajak kita melihat kembali bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga soal keberanian menjaga filosofi hidup sebagai fondasi moral, spiritual, dan sosial masyarakat Mimika.
Makna Filosofis Eme Neme Yauware
Dalam bahasa Amungme dan Kamoro, Eme Neme Yauware berarti Bersatu, Bersaudara, Membangun. Filosofi ini adalah sistem nilai hidup yang dianut masyarakat adat. Ia mewakili pentingnya gotong royong, keseimbangan relasi antarmanusia, serta keharmonisan dengan alam dan leluhur.
Suku Amungme yang tinggal di pegunungan dan suku Kamoro di pesisir telah lama hidup berdampingan dengan prinsip kolaborasi dan saling menghormati. Nilai-nilai ini termanifestasi dalam struktur sosial, adat, dan rumah adat mereka seperti Karapao dan Honai, yang melambangkan tempat berkumpul yang harmonis, rumah sejati dengan aturan moral, tata tertib sosial, dan nilai spiritual.
Mengubah semboyan ini bukan sekadar soal bahasa, melainkan berisiko merombak nilai dasar yang telah membentuk pola pikir dan cara hidup masyarakat Mimika selama berabad-abad.
Kritik Terhadap “Mimika Rumah Kita”
Pengenalan jargon ‘Mimika Rumah Kita’ oleh Pemerintah Kabupaten Mimika menuai kritik keras. Rafael Taurekeyau, Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK), menegaskan penolakannya. Menurutnya, Eme Neme Yauware adalah harga diri dan simbol sah milik masyarakat Amungme dan Kamoro. Menggantinya adalah bentuk pengaburan sejarah dan identitas budaya (CEPOS, 18/09/2025).
Tokoh adat Kamoro, Laurens Minipko, menyebut rumah sejati bagi masyarakat Mimika adalah Karapao dan Honai yang berdiri atas nilai Eme Neme Yauware. Rumah yang kuat harus memiliki aturan moral dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Nilai-nilai ini tidak bisa diganti hanya dengan istilah baru yang belum berakar budaya.
Anggota DPR Papua Tengah asal Mimika, Urbanus Beanal, menegaskan bahwa Mimika bukan tanah kosong yang bisa diberi identitas baru sesuka hati.
“Nama Eme Neme Yauware memiliki makna dan sejarah bagi masyarakat asli Mimika. Jangan diganti hanya karena kepentingan sesaat” (CEPOS, 16/09/2025).
Respons Pemerintah
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa Eme Neme Yauware tidak pernah diganti. Menurutnya, Mimika Rumah Kita hanyalah tagline program, bukan moto pengganti.
“Eme Neme Yauware tetap semboyan resmi Kabupaten Mimika. Ini adalah warisan dan filosofi hidup masyarakat Amungme-Kamoro yang tidak mungkin dihapus” (CEPOS, 18/09/2025).
Pj. Sekda Mimika, Abraham Kateyau, juga menegaskan hal yang sama. Ia menyebut anggapan bahwa Eme Neme Yauware diganti atau dihapus adalah keliru dan salah besar.
“Pemikiran ini tidak benar dan salah besar. Keliru. Eme Neme Yauware adalah semboyan Mimika, filsafat Mimika yang tidak dirubah,” tegasnya (FajarPapua, 17/09/2025).
Menurut Kateyau, Mimika Rumah Kita hanyalah tagline atau brand daerah yang lahir dari konsep Mimika Smart City. Slogan lengkapnya berbunyi: Mimika Rumah Kita, Negeri Seribu Sungai dan Sejuta Bakau. Ia menjelaskan bahwa Mimika adalah rumah orang Kamoro dan Amungme; Honai dan Karapao. Sebagai tuan rumah, mereka menyambut banyak orang dengan berbagai budaya, agama, dan bahasa untuk hidup bersama. “Maka kita semua harus jaga rumah ini bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kateyau menekankan adanya semangat Eme Neme Yauware dalam konsep rumah bersama ini. Seperti filosofi orang Kamoro, we iwoto, tapare iwoto, yang mengandung nilai kebersamaan. (FajarPapua, 17/09/2025).
Filosofi Hidup dan Filsafat
Filosofi bukan sekadar kumpulan kata bijak, tetapi kerangka berpikir yang membantu cara manusia memahami dunia dan mengatur kehidupannya. Karena itu, ketika masyarakat Mimika berpegang pada Eme Neme Yauware, kita tidak sedang berbicara tentang sebuah slogan, melainkan tentang fondasi moral dan eksistensial yang menyatukan mereka selama berabad-abad.
Socrates pernah berkata bahwa “kehidupan yang tidak dipertanyakan tidak layak dijalani”. Artinya, nilai hidup yang diwariskan turun-temurun perlu terus direnungkan dan dipelihara. Filosofi Eme Neme Yaware adalah hasil perenungan kolektif yang sudah teruji oleh waktu, krisis, dan sejarah panjang masyarakat Amungme dan Kamoro.
Confucius menekankan pentingnya keharmonisan, keseimbangan sosial, dan etika dalam membangun masyarakat yang stabil. Nilai ini tercermin jelas dalam Eme Neme Yaware, yang menekankan persaudaraan dan kebersamaan sebagai dasar pembangunan.
Dalam perspektif modern, Jürgen Habermas melihat ruang publik sebagai arena dialog dan negosiasi makna sosial. Mimika Rumah Kita mungkin dipandang sebagai upaya membangun ruang publik baru yang lebih inklusif, tetapi dialog tersebut hanya sahih bila tetap berakar pada fondasi lokal, yaitu Eme Neme Yaware. Tanpa akar itu, ruang publik justru rapuh dan kehilangan legitimasi budaya.
Lebih jauh, Hegel dalam dialektikanya menekankan pentingnya Geist (roh/semangat) yang menggerakkan suatu bangsa. Dalam konteks Mimika, Eme Neme Yaware adalah roh kolektif masyarakat adat, semacam Volksgeist Papua Tengah yang tidak bisa diganti begitu saja oleh jargon modern yang belum mengakar.
Sementara itu, teori keadilan John Rawls dengan konsep justice as fairness mengingatkan bahwa pembangunan harus menjamin keadilan bagi yang paling rentan. Jika moto asli masyarakat adat diabaikan, maka keadilan substantif yang diidealkan Rawls justru gagal diwujudkan, karena identitas dan hak masyarakat adat tidak menjadi pusat pembangunan.
Martin Heidegger menegaskan pentingnya being (ada) yang otentik. Masyarakat Mimika tidak sekadar membutuhkan slogan baru, melainkan pengakuan atas keberadaan mereka yang otentik sebagai pemilik tanah, sejarah, dan filosofi hidup. Eme Neme Yaware menjadi jalan menuju eksistensi otentik itu, yang tidak boleh ditutupi oleh jargon modernitas yang dangkal.
Dengan demikian, bila dilihat dari berbagai perspektif filsafat klasik maupun modern; Eme Neme Yaware bukan hanya sebuah semboyan, melainkan fondasi etis, ontologis, dan politik yang mengikat masyarakat Mimika. Menggantinya atau mengaburkan makna itu sama saja dengan merobohkan rumah dari fondasinya.
Ketimpangan Ekonomi dan Pembangunan
Kabupaten Mimika merupakan daerah industri besar sejak hadirnya PT Freeport Indonesia tahun 1973. Belakangan, perusahaan lain seperti LNG Tangguh di Bintuni dan PetroChina di Sorong juga hadir. Namun, realitas sosial di Tanah Papua tidak mencerminkan kekayaan alam yang dihasilkan. Hingga 2025, enam provinsi di Tanah Papua masih termasuk daerah termiskin di Indonesia (BPS, 2024).
Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam industri dan pemerintahan. Mayoritas tenaga kerja perusahaan besar adalah pendatang karena sebagian besar proses rekrutmen dilakukan di Pulau Jawa, sementara OAP hanya menduduki posisi terbatas. Padahal, masyarakat adat adalah pemilik sah tanah dan sumber daya tersebut. (Salam Papua 19/9/2025).
Hal ini menunjukkan bahwa filosofi pembangunan nasional masih menempatkan masyarakat adat sebagai objek, bukan subjek. Yang perlu diubah bukan Eme Neme Yaware, melainkan filosofi pembangunan yang harus menempatkan masyarakat adat sebagai pusatnya.
Adat Sebagai Aktor Utama
Polemik pergantian semboyan sejatinya mencerminkan perdebatan lebih dalam tentang arah pembangunan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap nilai lokal. Eme Neme Yauware adalah filosofi hidup yang sudah mengakar kuat. Ia merepresentasikan persatuan dan pembangunan masyarakat adat, sehingga tidak perlu diubah.
Yang harus dikoreksi adalah cara pandang pembangunan yang tidak adil. Pemerintah daerah dan pusat harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, yang terlibat aktif dan memperoleh manfaat adil dari sumber daya alam.
Dengan menjaga nilai luhur Eme Neme Yauware sebagai roh pembangunan, sekaligus membuka ruang dialog inklusif dan praktik pembangunan yang adil, Mimika bisa benar-benar menjadi rumah bersama. Bukan sekadar jargon, melainkan kenyataan sosial dan ekonomi yang berpihak pada masyarakat adat. (Isi tulisan tanggung jawab penulis)